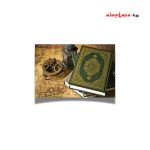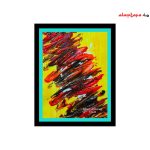Ketika mendengar atau membaca tentang konsep sab’ah ahruf, kita sering mengira itu sama dengan konsep qira’ah sab’ah. Istilah sab’ah ahruf dan qira’ah sab’ah merupakan pembahasan dalam ulumul Qur’an. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, namun saling berkaitan. Pembahasan mengenai qira’ah sab’ah tidak bisa terlepas dari pembahasan sab’ah ahruf. Karena sab’ah ahruf menjadi bagian dari sebab munculnya qira’ah sab’ah.
Akan tetapi, istilah qira’ah sab’ah muncul bukan semata-mata karena sab’ah ahruf, artinya, istilah sab’ah ahruf muncul ketika Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, sementara qira’at sab’ah muncul karena dilatarbelakangi beragamnya bacaan Imam Qurra’ dalam membaca Al-Qur’an yang dihimpun menjadi tujuh Imam (Suarni, 2018: 167).
Konsep ini sudah baku (mutawatirah). Dalam artian, jelas periwayatan yang bersumber dari Nabi serta tak terdapat cacat di setiap kontinuitas sanadnya. Karena itu, jika kemudian setiap dialek dan bahasa yang ada di seluruh daerah di dunia ini membuat konsep yang serupa, maka itu tidak dapat diterima.
Pengertian Sab’ah Ahruf
Secara etimologis, sab’ah ahruf berarti tujuh huruf. Secara terminologis, sab’ah ahruf dapat dipahami bahwa Al-Qur’an diturunkan dalam tujuh dialek bahasa Arab, sehingga kemudian melahirkan ragam cara baca Al-Qur’an atau yang dikenal qira’ah sab’ah (tujuh cara baca), dalam versi lain ada qira’ah ‘asyirah (sepuluh cara baca).
Dari kenyataan di atas mengindikasikan bahwa sejak awal kehadirannya, Al-Qur’an menjadi kitab universal yang tidak serta-merta menolak perbedaan yang ada di tengah umat. Persatuan umat dibangun atas kesadaran bahwa kita sama-sama berbeda. Dari spirit tersebut lahir sikap terbuka dan saling menerima.
Identitas Masyarakat Arab
Jauh sebelum Islam datang, bangsa Arab adalah bangsa yang terbagi dari berbagai kabilah. Itu sebabnya mereka memiliki keragaman bahasa dan budaya. Pada satu sisi, mereka dikenal dengan wataknya yang keras juga fanatik. Tapi pada sisi yang lain, masyarakat Arab sangat identik dengan peradaban teks. Kesenangan mereka tercurahkan pada syair–syair ataupun puisi yang memiliki nilai–nilai kesastraan bahasa yang tinggi.
Syair-syair tersebut dijadikan sebagai identitas keahlian, kehormatan, dan simbol glorifikasi kabilah masing-masing. Salah satu tradisi mereka misalnya, mengadakan kontes keindahan syair di pasar yang dikenal Suq ‘Ukaz. Nantinya setiap syair yang terindah akan ditempelkan di dinding ka’bah.
Dinamika kontestasi juga saling mengkritisi bahasa bukanlah hal yang tabu pada waktu itu, melainkan sebuah keharusan yang sudah membudaya. Para kritikus bahasa dan sastra sangat gemar mengkritik setiap kemunculan bahasa dan syair baru (Ahmad Mustofa, 2018: 70).
Budaya mengkritisi seperti yang disebutkan di atas terus berlangsung sampai Al-Qur’an diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga tidak bisa dipungkiri, bahwa kemudian Al-Qur’an juga mendapat kritikan pedas dari orang-orang Arab. Walau demikian, i’jaz lughawi Al-Qur’an mampu menundukkan para kritikus sastra Arab. Bahkan Al-Qur’an men-callenge balik mereka, dan buktinya tidak ada yang mampu menandingi keistimewaan uslub bahasa Al-Qur’an (QS. al-Baqarah/2: 23).
Interaksi Al-Qur’an dengan Realitas
Dengan banyaknya kabilah yang ada, maka dialek pun beragam, karena setiap kabilah memiliki perbedaan dialek bahasa. Beberapa sahabat Nabi membaca Al-Qur’an dengan dialek kabilah mereka sendiri. Hal ini menjadi latar belakang munculnya perbedaan dalam membaca Al-Qur’an. Namun kendati demikian, setiap bacaan yang diriwayatkan dari sahabat adalah shahih hukumnya, dikarenakan mereka men-talaqqi-kan bacaan itu di hadapan Nabi secara langsung.
Dari kenyataan di atas membawa konsekuensi terhadap Al-Qur’an yang mengafirmasi, dan pada tahap selanjutnya menggunakan ragam bahasa kabilah Arab. Indikasi yang menuturkan bahwa Al-Qur’an berinteraksi dengan bahasa-bahasa kabilah Arab (lokal) adalah hadits Nabi yang menyebut “Sab’ah Ahruf”. Banyak interpretasi yang diapresiasikan oleh para pakar ulumul Qur’an mengenai sabda Nabi tersebut.
Namun di antara pendapat yang kuat seperti al-Suyuthi (w. 1505) dalam al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, dan al-Qaththan (w. 1999) dalam Mabahits fi ‘Ulum al-Qur’an mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan “Sab’ah Ahruf” adalah beberapa bahasa kabilah Arab yang terbilang paling fasih, sedang angka tujuh dalam redaksi hadits itu bertujuan sebagai isyarat dari banyaknya jumlah dialek bahasa yang dimuat.
Dengan demikian, kehadiran Al-Qur’an dengan keragaman dialek bahasa yang ada di dalamnya, melahirkan sebuah konsep yang menyatukan seluruh kabilah–kabilah Arab yang menampakkan jarak antara yang satu dengan yang lainnya. Ini menjadi bagian dari i’jaz lughawi Al-Qur’an. Rasa senang dan kedekatan emosional karena dialek bahasanya yang dipakai menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Arab untuk menerima kehadiran Al-Qur’an.
Al-Qur’an Menyikapi Perbedaan
Konsep sab’ah ahruf dalam kajian Al-Qur’an ini menegaskan bahwa risalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw bukan hanya untuk satu golongan saja, juga bertujuan meniadakan subjektivitas kultural dan fanatisme kesukuan.
Disadari atau tidak oleh kita, bahwa umumnya kalangan komunitas agama menganut paham eksklusif, yaitu menganggap hanya pandangan dan kelompoknyalah yang paling benar. Pemahaman yang eksklusif ini telah meninggalkan jejak sejarah yang kelam, membawa citra buruk agama yang bercorak konflik dan kekerasan. Hal tersebut sungguh menyalahi spirit Al-Qur’an membebaskan manusia dari belenggu fanatisme dan klaim kebenaran berdasarkan subjektivitas kultural.
Dengan beragamnya dialek bahasa kabilah yang dirangkul oleh Al-Qur’an, melahirkan pandangan bahwa kitab ini mengandung ajaran yang inklusif untuk semua kalangan tanpa mempermasalahkan perbedaan sebagaimana misi Al-Qur’an sendiri yaitu rahmatan lil ‘alamin. Spirit ini mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan bukanlah sebuah masalah yang dapat menjerumuskan kita pada sikap fanatik dan saling membenci sesama.
Demikian pula menegaskan bahwa bahasa Al-Qur’an juga bukanlah bahasa milik satu golongan (Arab) saja, sebab setiap kabilah merasa memiliki Al-Qur’an dikarenakan terdapat dialek bahasa mereka di dalamnya. Dari kenyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa Al-Qur’an merupakan kitab universal bagi umat Islam dari berbagai bangsa, ras, suku, dan golongan.
Lisanun ‘Arabiyyun dalam surah an-Nahl/16 ayat 103, menurut para pakar, tidak dalam rangka mengkultuskan satu bahasa, tapi lebih kepada mempertegas bahwa bahasa yang digunakan dalam kitab ini bukanlah bahasa non-Arab, juga sekaligus menyangkal bahwa Al-Qur’an bagian dari hasil tangan Nabi meniru kitab-kitab suci sebelumnya sebagaimana yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad Saw (Egi Sukma Baihaki, 2017: 48).
Refleksi
Konsep sab’ah ahruf ini menjadi bukti bahwa Al-Qur’an sesungguhnya merawat perbedaan (yang menjadi sebuah keniscayaan) dalam rangka fastabiqul khairat (mengamalkan kebaikan yang plural), dengan cara menghormati setiap perbedaan yang ada serta terdapat dialektika konstruktif-positif antara kearifan lokal masyarakat dengan Al-Qur’an itu sendiri.
Hal ini juga memberikan kekuatan tersendiri bagi umat Islam untuk menjalin sebuah hubungan satu kesatuan dalam ruang ukhuwah Islamiyah dan Insaniyah, khususnya dalam konteks ke-Indonesia-an kita yang majemuk, kini hingga nanti.[]
Ilustrasi: www.sonora.id

Penulis di Sarangge Kahawa Institut dan meminati kajian al-Qur’an