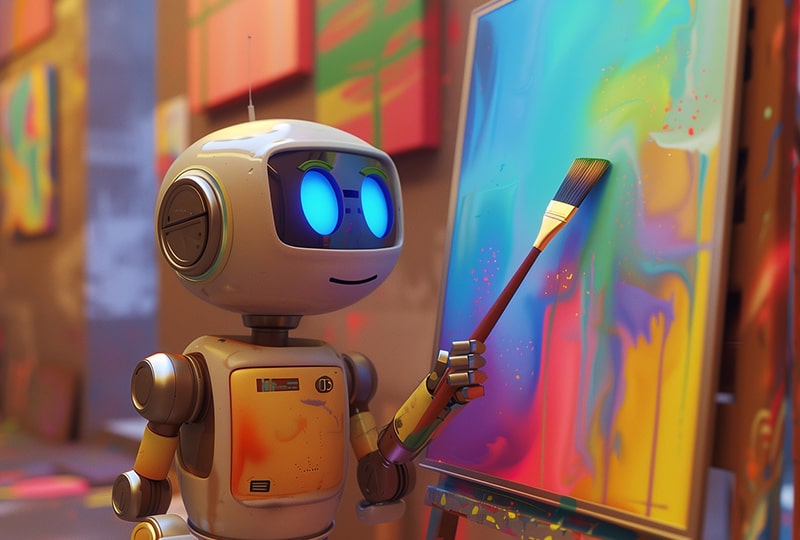Selama ribuan tahun, agama kerap dipersepsikan sebagai sesuatu yang statis, pilar tradisi yang berdiri teguh melawan arus perubahan zaman. Namun, pandangan itu mulai goyah ketika kita menelusuri hubungan antara agama dan media. Faktanya, agama justru sangat adaptif terhadap teknologi komunikasi. Setiap kali manusia menemukan cara baru untuk berkomunikasi, dari prasasti batu kuno hingga kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), selalu muncul bentuk baru dari “teknologi sakral” yang mengubah cara manusia beriman, beribadah, dan berinteraksi. Media tidak hanya menjadi alat penyampai pesan agama, melainkan bagian dari pengalaman spiritual itu sendiri.
Artikel ini mengajak kita menelusuri babak revolusi media yang telah membentuk wajah keberagamaan modern, dari arsitektur megah yang memancarkan kemuliaan Tuhan hingga ruang algoritma yang sunyi namun penuh gema keyakinan iman.
Agama dalam Bingkai Jurnalisme: Antara Konflik dan Kemanusiaan
Hubungan antara agama dan media massa tidak pernah benar-benar netral. Melalui pembingkaian (framing), media memiliki kekuatan untuk mendefinisikan bagaimana agama dipersepsikan publik. Dalam praktiknya, jurnalisme sering memandang agama melalui kerangka konflik, menggambarkannya sebagai sumber kekerasan, pertentangan, atau perpecahan, sebab berita seperti itu mendatangkan perhatian dan klik yang tinggi.
Namun, sesekali muncul pula kerangka minat manusia, di mana agama dipotret lewat kisah pribadi dan spiritualitas yang hangat. Sayangnya, kerangka ini sering kalah kuat dari narasi konflik yang lebih sensasional. Banyak redaksi besar mengakui tidak memiliki koresponden khusus agama, bahkan ada editor yang terang-terangan mengatakan bahwa mereka “tidak memahami agama”. Akibatnya, isu-isu keagamaan kerap diberitakan secara dangkal, muncul hanya ketika bersinggungan dengan politik atau hak asasi manusia. Di bawah tekanan ekonomi media, agama pun lebih sering tampak sebagai masalah sosial ketimbang sumber moralitas dan makna.
Gema dari Masa Lalu: Revolusi Cetak dan Arsitektur Sakral
Sebelum dunia mengenal layar digital, revolusi media cetak telah mengguncang tatanan keagamaan global. Penemuan mesin cetak Gutenberg menandai titik balik besar. Sebelumnya, Gereja Katolik memegang kendali penuh atas teks suci. Alkitab hanya tersedia dalam bahasa Latin dan sulit diakses masyarakat umum. Mesin cetak mengubah semuanya. Ketika Alkitab diterjemahkan ke bahasa lokal dan dicetak massal, otoritas keagamaan berpindah dari institusi menuju individu. Dari sinilah lahir Reformasi Protestan, simbol lahirnya era baru kebebasan spiritual.
Namun, bahkan sebelum tinta dan kertas mendominasi, manusia sudah membangun media visual keagamaan melalui arsitektur sakral. Katedral abad pertengahan adalah “media raksasa” yang mengajarkan iman lewat bentuk dan cahaya. Jendela kaca patri menjadi “Alkitab bagi yang buta huruf”, menyampaikan kisah suci melalui warna dan cahaya. Kini, bentuk itu berevolusi: mega-gereja modern menyerupai teater atau stadion, di mana tata ruang dirancang untuk mendukung teknologi audio-visual. Arsitektur tidak lagi hanya simbol iman, tetapi juga alat penyiaran spiritualitas.
Era Penyiaran: Dari Panggung ke Skandal
Ketika radio dan televisi hadir, mimbar keagamaan berpindah ke ruang keluarga. Radio membawa pesan spiritual langsung ke rumah-rumah, dan tokoh karismatik seperti Aimee Semple McPherson menjadikan khotbah sebagai pertunjukan. Era televisi kemudian melahirkan fenomena televangelisme di mana pemuka agama menjelma menjadi selebritas global yang beroperasi di pasar iman.
Namun, media yang sama juga membuka sisi gelap kekuasaan rohani. Kekayaan dan pengaruh besar yang mereka peroleh sering berujung pada penyalahgunaan. Liputan media terhadap kasus pelecehan seksual dalam Gereja Katolik memperkuat fungsi media sebagai pengawas moral, memaksa institusi agama untuk bertanggung jawab atas dosa-dosa yang selama ini tersembunyi di balik altar.
Kebangkitan Digital: Demokratisasi dan Polarisasi
Lompatan berikutnya datang bersama Internet, yang membawa demokratisasi paling radikal dalam sejarah agama. Kini, siapa pun bisa menjadi “otoritas spiritual” selama memiliki pengikut dan tampilan yang menarik. Komunitas beriman terbentuk lintas geografis, menembus batas-batas denominasi dan bahasa. Bahkan lembaga konservatif seperti Vatikan telah memanfaatkan media sosial untuk menjangkau lebih dari satu miliar orang.
Pandemi COVID-19 menjadi katalis yang mempercepat transformasi ini. Ibadah daring dan pastoral digital menjadi norma baru. Di sisi lain, platform seperti TikTok melahirkan influencer agama yang mengemas ajaran suci lewat tren viral. Mereka menampilkan sisi manusiawi iman—namun juga menimbulkan komodifikasi agama, di mana spiritualitas dikonversi menjadi konten berbayar dan merchandise.
Sayangnya, algoritma media sosial menciptakan gelembung keyakinan. Kita lebih sering berinteraksi dengan mereka yang sepemahaman, terperangkap dalam ruang gema digital yang memperkuat polarisasi dan menekan dialog lintas iman. Dalam ekosistem seperti ini, empati semakin menipis, sementara ekstremisme menemukan panggung baru yang tak terbatas.
Kasus Indonesia: Ketika Representasi Agama Berhadapan dengan Logika Media
Fenomena ini tampak jelas dalam peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Pada Oktober 2025, sebuah program di stasiun televisi Trans7 menuai kecaman publik setelah menayangkan segmen yang dianggap melecehkan Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri, salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di negeri ini. Tayangan tersebut memuat narasi yang menggambarkan relasi kiai dan santri secara keliru, bahkan menyinggung adab kehidupan pesantren yang selama ini dihormati masyarakat luas.
Gelombang reaksi pun muncul dengan cepat. Dalam hitungan jam, tagar #BoikotTrans7 menjadi trending di media sosial. Ribuan alumni dan santri Lirboyo menuntut permintaan maaf terbuka, sementara berbagai tokoh agama dan lembaga keislaman menyerukan agar media nasional lebih berhati-hati dalam merepresentasikan dunia pesantren. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) turut menyoroti tayangan itu sebagai bentuk ketidaksensitifan terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual lokal. Trans7 akhirnya mengeluarkan permintaan maaf resmi dan berjanji memperbaiki mekanisme editorialnya.
Peristiwa ini menunjukkan dua hal penting. Pertama, media massa arus utama masih memiliki kekuatan membentuk persepsi publik tentang agama dan institusinya. Cara suatu lembaga keagamaan ditampilkan di layar dapat mengubah wajahnya di benak masyarakat—apakah tampak agung, ketinggalan zaman, atau bahkan eksploitatif. Kedua, kasus ini memperlihatkan bagaimana revolusi media digital mengubah keseimbangan kekuasaan. Jika dulu lembaga agama hanya bisa menerima bingkai pemberitaan, kini mereka dapat menanggapi, memobilisasi dukungan, dan membalik narasi melalui jejaring digital yang luas.
Dalam konteks inilah, kita melihat bahwa demokratisasi media membawa paradoks, yaitu di satu sisi membuka ruang partisipasi publik yang luas dalam menafsirkan agama, di sisi lain menimbulkan risiko distorsi makna ketika logika hiburan dan sensasi menggantikan sensitivitas spiritual. Maka, tantangan terbesar umat beragama di era digital bukan lagi bagaimana menghadirkan agama di media, melainkan bagaimana menjaga makna suci di tengah derasnya arus medialisasi.
Masa Depan AI: Antara Ancaman dan Janji
Kini kita tiba pada babak paling mutakhir, era kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini berpotensi merevolusi pengalaman spiritual. Bayangkan AI Spiritual Guide yang mampu menjawab pertanyaan teologis berdasarkan teks suci, atau ziarah realitas virtual yang memungkinkan seseorang “hadir” di Mekkah, Yerusalem, atau Bodhgaya (tempat suci umat Buddha) tanpa berpindah tempat. Batas antara iman dan imajinasi menjadi semakin kabur.
Namun, di sinilah muncul pertanyaan besar: Apakah AI adalah agama baru? Sebagian futuris melihat AI sebagai entitas “maha tahu dan maha hadir” yang nyaris menyerupai Tuhan. Bagi sebagian orang, AI adalah janji “surga duniawi” yang dibangun di atas kode, bukan kitab. Pertanyaan tentang jiwa, kesadaran, dan makna kemanusiaan pun kembali menggema.
Institusi keagamaan mencoba menanggapi dengan hati-hati. Ada yang melihat AI sebagai sarana dakwah modern, sementara Vatikan menyoroti aspek etika, menuntut agar pengembangan AI tetap menempatkan manusia dan kemaslahatan sosial di pusatnya.
Penutup
Perjalanan panjang agama bersama media menunjukkan satu hal: teknologi selalu bersifat ambivalen. Ia dapat menjadi alat pencerahan sekaligus sumber polarisasi. Ia mendekatkan umat, tapi juga menciptakan jurang di antara mereka. Namun di atas segalanya, kisah ini menegaskan bahwa agama bukanlah korban zaman—melainkan penjelajah spiritual yang terus menafsir ulang dirinya di tengah perubahan cara manusia berkomunikasi.
Setiap inovasi, dari lempeng batu hingga AI, memaksa kita untuk menanyakan kembali: apa arti iman di dunia yang terus berubah ini?
*Artikel adalah catatan perkuliahan yang diikuti penulis di kelas Cultur, Soiety and Religion dengan dosen Prof. Dr. Natan Womack University of California Riverside (UCR)
Mahasiswa Doktoral PTIQ Jakarta Peserta Short Course PKUMI di UCR USA