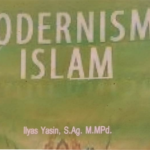Pada tanggal 26 Agustus 2020, saya berada satu forum dengan Budhy Munawar Rachman dan Wahyuni Nafis dalam acara peluncuran dan bedah Buku “Karya Lengkap Nurcholish Madjid”. Buku ini adalah kumpulan dari semua karya yang pernah ditulis oleh Nurcholish Madjid (Cak Nur) semasa hidupnya. Buku ini sangat tebal yaitu terdiri dari 5000 lebih halaman.
Saya diminta untuk membedah buku ini khusus untuk menemukan isu humanisme dan kesetaraan gender di dalam karyanya tersebut. Tidak mudah bagi saya membaca buku tebal tersebut dalam waktu yang kurang dari sebulan setelah dikirimkan bukunya oleh panitia acara. Membaca bukan sekedar untuk membunuh waktu tetapi untuk menemukan mutiara pemikiran Cak Nur pada dua topik penting tersebut.
Untuk mempermudah membaca buku ini, ada dua hal yang saya lakukan. Pertama, membaca dengan seksama pengantar buku. Saya sangat tertolong oleh pengantar yang ditulis oleh Budhy Munawar Rachman. Pengantar tersebut berhasil memetakan periodesasi pemikiran Cak Nur yang dibagi ke dalam dua periode.
Periode pertama (1965-1978) yang merupakan tahap keislaman dan dan keindonesiaan. Di mana, rasionalisme menjadi kata kunci dengan penegasan rasionalisme bukan westernisme. Periode kedua (1984-2005) yaitu tahap keislaman dan kemodernan. Sedangkan 1978-1984 itu masa-masa Cak Nur menuntut ilmu di Chicago. Meminjam teori Kurzman tentang liberal, silent, dan interpreted syariah, Budhy Munawar Rachman juga dengan apik mengidentifikasi warna dan topik diskusi di dalam tulisan Cak Nur.
Kedua, membaca dengan kata kunci. Saya terbantukan dengan buku elektronik yang dikirim oleh panitia karena bisa mencari kata kunci dengan mudah melalui aplikasi find. Saya awalnya memasukkan kata kunci “humanisme” dan “kesetaraan gender”.
Jika kata yang pertama muncul pada hampir semua tulisan Cak Nur, tetapi kata “kesetaraan gender” tidak ada sama sekali. Oleh karena itu langkah selanjutnya, saya mencoba beberapa kata yang dekat atau terkait dengan humanisme, misalnya kemanusiaan, keadilan, HAM, emansipasi, dan emansipatoris. Beberapa kata kunci inilah kemudian yang menjadi starting point bagi saya untuk menemukan intisari pemikiran Cak Nur tentang humanisme dan kesetaraan gender.
Membaca Cak Nur dari Jauh
Berbeda dengan Budhy Munawar Rachman dan Wahyuni Nafis yang mengenal Cak Nur secara personal dan lama berinteraksi dengan beliau maupun karya-karya beliau, saya adalah pembaca baru Cak Nur dan dari jauh. Semasa kuliah S1 yaitu tahun 1993-1997, masa-masa pemikiran Cak Nur membahana di seantero negeri bahkan di level internasional, saya hanya pernah membaca dua buku Cak Nur yaitu “Islam, Keindonesiaan, dan Kerakyatan” dan “Pintu-pintu Menuju Tuhan”.
Sedangkan buku Cak Nur yang lain Islam, Doktrin, dan Peradaban, hanya saya baca setengah-setengah dan sambil lalu saja. Padahal buku ini adalah magnum opus beliau. Sesuatu yang belakangan saya sesali sekaligus syukuri.
Menyesal, mengapa saya melewatkan pemikiran tokoh besar ini di saat yang tepat. Bersyukur, karena sebenarnya dua buku yang saya baca tersebut membuat saya justru meragukan isu dan rumor yang ‘menuduh’ Cak Nur adalah tokoh Islam yang sekuler yang sudah mengalami proses brainwashing setelah menempuh pendidikan di Barat. Bukunya, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, sama sekali tidak mengesankan Cak Nur dengan berbagai tuduhan itu. Buku itu justru mengungkap sisi sufisme dalam diri Cak Nur yang saya kesankan sebagai orang yang sangat religius.
Saat kuliah, saya menambah pengalaman organisasi di PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) di mana pemikiran Gus Dur lebih banyak diakses. Berbeda misalnya dengan para aktivis HMI yang jauh lebih akrab dengan pemikiran Cak Nur. Ternyata pilihan berorganisasi juga menjadikan saya berjarak dengan pemikiran Cak Nur. Pilihan yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi.
Jadi intisari yang saya sampaikan dalam acara bedah buku tersebut harus dipahami dalam konteks dan posisi tersebut. Sehingga apa yang saya sampaikan bisa jadi naif tetapi juga bisa juga dipandang autentik karena “jarak” dalam banyak hal dapat mengeleminir subyektivitas.
Humanisme ala Cak Nur
Ada tiga pasang konsep yang perlu dipahami sebagai basis epistemologis di dalam memahami humanisme Islam yang dijelaskan oleh Cak Nur yaitu tauhid dan keimanan, teosentris dan antroposentris, serta agama dan sains.
Tauhid dan keimanan harus mengandung definisi ideologis sekaligus operasional. Secara ideologis, tauhid bermakna melihat bahwa Allah itu Esa. Hanya satu. Tidak ada kekuasaan dan zat yang berkuasa terhadap hidup seseorang kecuali Allah Sang Pencipta. Secara operasional, tauhid harus terimplementasi di dalam kehidupan sehari-hari yaitu menolak ketundukan kepada siapa pun di luar zat yang Esa itu.
Manusia yang satu terhadap manusia lainnya dalam posisi yang setara, sehingga berdasarkan tauhid, tidak diperbolehkan adanya penguasaan dan kepemilikan terhadap manusia lainnya. Orang yang bertauhid oleh karenanya tidak akan menguasai orang lain dan sebaliknya tidak gampang tunduk dikuasai oleh orang lain.
Iman bermakna percaya. Percaya terhadap Allah, kitab, rasul, malaikat, hari akhirat dan takdir baik dan buruk. Tetapi iman juga seakar kata dengan aman dan amanah. Jadi orang yang beriman harus memiliki sikap yang membuat dirinya sendiri aman dan orang lainnya merasa aman.
Salah satu sikap agar orang lain aman itu adalah amanah yaitu jujur dan dapat dipercaya. Tidak manfaat seseorang beriman kalau tidak menghadirkan sikap amanah sehingga orang lain tidak merasa aman. Jadi tauhid dan iman ini sebenarnya berfungsi untuk mengemansipasi manusia, bahwa manusia setara dan harus saling menjaga.
Teosentris dan antroposentris adalah karakter Islam yang tidak dapat dipisahkan. Teosentris adalah pandangan hidup yang menjadi episentrum dari kegiatan hidup. Kegiatan hidup ini harus menjadikan manusia sebagai pusat. Apa yang dilakukan oleh manusia harus memberikan dampak positif bagi manusia lainnya.
Agar bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat ini manusia harus memusatkan pandangannya pada aturan Tuhan (teosentris). Jadi Tuhan tetap menjadi dasar yang tidak bisa ditawar, tetapi dasar ketuhanan ini harus memastikan kebermanfaatan bagi kemanusiaan di dalam kehidupan sosialnya.
Agama dan science. Islam dan pengetahuan saling memperkuat, tidak saling menegasi. Dalam penjelasannya tentang keterkaitan ini, Cak Nur melihat bahwa wahyu atau agama memberikan tugas kepada akal untuk mencerna makna dan kandungannya. Akal yang melahirkan pengetahuan oleh karenanya adalah upaya menjelaskan agama ke dalam kehidupan.
Oleh karena itu, Islam menurutnya, sama sekali tidak bertentangan dengan isme-isme baru yang lahir dari kemodernan misalnya demokrasi, Hak Asasi Manusia, pluralisme, inklusivisme, tetapi bisa berdialog untuk menghasilkan argumen yang religius sekaligus akademik. Islam meletakkan penggunaan akal pada posisi yang terhormat.
Kesetaraan Gender dalam Pandangan Cak Nur
Dalam karya lengkapnya ini, Cak Nur sebenarnya tidak berbicara khusus tentang kesetaraan gender dan perempuan. Tetapi pandangannya terkait humanisme Islam sebagaimana yang dijelaskan di atas telah meletakkan dasar epistemologi bagi pemikiran dan aksi kesetaraan gender.
Paling tidak ada tiga tulisan Cak Nur dalam buku ini yang juga menggambarkan bagaimana pandangannya tentang kesetaraan manusia termasuk kesetaraan gender yaitu:
Pertama, Keadilan: Iman dan Emansipasi Harkat Kemanusiaan pada halaman 625. Pada tulisannya ini Cak Nur kembali menegaskan bahwa keimanan dan ketauhidan yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Esa harus membuat manusia merasa setara satu sama lain terutama pada level harkat dan derajatnya. Perbedaan yang terjadi karena struktur sosial yang mengharuskan bukan alasan untuk melihat manusia tidak sama.
Pada konsep keadilan sosial yang Cak Nur pahami adalah bukan berarti manusia memiliki kekuatan dan akses yang sama karena pasti ada yang lemah ada yang lebih memiliki kesempatan, misalnya pada perkara zakat. Islam telah menugaskan manusia untuk mengisi kelemahan kelompok lain oleh kelompok yang lebih kuat dengan mendistribusikan kekayaannya atau akses ekonomi kepada mereka.
Dalam hal ini, institusi zakat memastikan bahwa yang kuat dan yang lemah pada akses akan menikmati hasil yang sama, di mana yang kuat tidak boleh memonopoli dan mengenyampingkan fakta bahwa ada kelompok lain yang perlu disantuni.
Kedua, Egalitarianisme: Pidato Kemanusiaan pada halaman 4739. Cak Nur menjelaskan pidato Nabi pada haji Wada’ (haji perpisahan) menjelang berpulang ke Tuhan-Nya. Pidato ini menegaskan persamaan manusia dan perintah melakukan kebaikan dan penghormatan terhadap istri dan kaum perempuan. Bahwa istri dan suami masing-masing memiliki hak dan kewajiban, hak yang satu adalah kewajiban bagi yang lainnya.
Sepanjang hidupnya, Nabi telah mencontohkan lewat perbuatan maupun menjelaskan lewat perkataannya tentang akhlak kepada perempuan dan istrinya. Maka pada pidato yang disampaikan pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H di Lembah Uranah Gunung Arafah itu memastikan bahwa hal ini sangat penting untuk diperhatikan sebagai wasiat terakhir beliau untuk umatnya.
Ketiga, Perempuan dan Perkawinan: Antara Prokreasi dan Rekreasi pada halaman 1371. Di sini Cak Nur berbicara tentang pandangannya terkait poligami. Menurutnya, poligami bisa dilakukan tergantung bagaimana seorang laki-laki memaknai perkawinannya.
Jika dilihat sebagai rekreasi atau lembaga yang menghalalkan pemuasan hawa nafsu, maka ia dengan gampang menyetujui dan melakukan poligami. Tetapi kalau ia melihatnya sebagai prokreasi, maka yang menjadi fokus di dalam pernikahannya adalah bagaimana menciptakan dan membimbing generasi dan menjadikan pernikahan sebagai akad yang kuat.
Cak Nur juga mempertegas bahwa keadilan terhadap perempuan memang harus di mulai dari lembaga pernikahan dan keluarga. Ini juga ia tegaskan dalam tulisannya yang lain yang berjudul “Pernikahan dan Keluarga”. Pokok pikiran yang sangat saya setujui.
Terima kasih Cak Nur![]

Direktur La Rimpu (Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan), Peneliti Perempuan dan Perdamaian, dosen UIN Mataram.