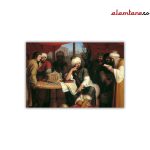Kadang kita merasa dunia ini terlalu ribut untuk dijalani dengan tenang. Semua orang berlomba mencari pembenaran, berlomba merasa paling benar, paling menderita, paling berhak. Dalam hiruk-pikuk itu, bersyukur terdengar seperti kata usang yang hanya cocok untuk pengajian ibu-ibu atau ceramah menjelang berbuka puasa. Padahal, kalau kita mau jujur, bersyukur justru adalah bentuk keberanian paling modern, paling revolusioner, dan—anehnya—paling waras di tengah dunia yang semakin tidak sabar mendengarkan satu sama lain.
Syukur bukan sekadar mengucap “alhamdulillah” dengan nada religius yang dipaksakan, melainkan cara berpikir yang melampaui keluhan dan rasa kekurangan. Ia adalah kesadaran eksistensial yang membuat manusia bertahan tanpa kehilangan arah. Dalam psikologi Islam, bersyukur ditempatkan sebagai puncak kesehatan spiritual. Menurut Prof. Malik Badri, seorang pionir psikologi Islam, syukur bukan hanya emosi positif, tetapi juga “penjernihan jiwa” yang membuat manusia terhubung dengan Tuhannya secara harmonis dan dengan sesamanya secara empatik. Ia menulis bahwa “jiwa yang bersyukur akan memandang segala sesuatu bukan dari apa yang hilang, tetapi dari apa yang tersisa dan masih bisa diperjuangkan.”
Dalam konteks sosial kita yang penuh konotasi negatif terhadap agama, sikap bersyukur menjadi cermin kewarasan. Kita hidup di zaman ketika agama sering dijadikan alat untuk menakut-nakuti, bukan menumbuhkan harapan; menjadi pagar pembeda, bukan jembatan penyatu. Orang beragama kadang lupa bahwa Tuhan yang disembah bukan hanya Tuhan bagi kelompoknya, tetapi Tuhan bagi seluruh makhluk yang Ia ciptakan. Bersyukur, dalam makna terdalamnya, adalah menolak menjadikan agama sebagai senjata untuk merasa paling suci. Ia adalah seni untuk menemukan makna, bukan alat untuk menilai orang lain.
Gus Paox Iben, pembina Pondok Kebudayaan Daarul Mudhofar dan Ruang Tumbuh Merdeka, pernah mengatakan bahwa “agama semestinya memberi bobot, bukan beban; memberi makna, bukan ketakutan.” Kalimat sederhana tapi menggigit ini, dalam tinjauan filosofis dan antropologis, mengandung kedalaman luar biasa. Bahwa agama hadir bukan untuk menambah kepanikan sosial, melainkan memperkaya jiwa manusia dengan kesadaran bahwa hidup—meski getir—selalu punya nilai untuk disyukuri. Jika kita mampu menemukan bobot makna dari setiap kejadian, bahkan dari luka dan krisis, maka di situlah letak kedewasaan spiritual.
Namun, realita sosial kita sering jelimet: agama dibenturkan dengan kemanusiaan, keyakinan dibenturkan dengan keberagaman, dan ketaatan dikerdilkan menjadi simbol sempit. Di tengah pusaran ini, bersyukur menjadi sikap anti-ekstrem paling elegan. Orang yang bersyukur tidak mudah diseret oleh ideologi kebencian, karena ia melihat dunia sebagai anugerah, bukan medan perang kebenaran. Ia menyadari bahwa kebenaran bukanlah kompetisi, melainkan perjalanan batin menuju ketenangan.
Dalam refleksi filosofis, syukur adalah bentuk kesadaran ontologis—cara manusia menyadari keberadaannya. Martin Heidegger mungkin menyebutnya sebagai Gelassenheit, yakni sikap menerima keberadaan sebagaimana adanya, tanpa kehilangan gairah untuk memperbaikinya. Dalam bahasa kita yang lebih membumi: bersyukur bukan berarti pasrah, melainkan memahami batas tanpa kehilangan semangat berjuang. Syukur mengajarkan keseimbangan—antara menerima takdir dan mengupayakan perubahan.
Dari sisi sosiologis, masyarakat yang kehilangan rasa syukur mudah terjebak dalam ekstremisme sosial dan keagamaan. Ketika orang tidak lagi mampu mensyukuri perbedaan, maka yang lahir adalah intoleransi. Ketika orang tidak mampu mensyukuri keberadaan dirinya, maka yang muncul adalah kekosongan makna yang mudah diisi oleh narasi kebencian. Dalam banyak kasus, ekstremisme berakar dari rasa tidak cukup—tidak cukup benar, tidak cukup dihargai, tidak cukup dimengerti. Padahal, rasa cukup adalah inti dari syukur.
Bersyukur berarti mengakui bahwa hidup tidak harus sempurna untuk layak dijalani. Ia adalah bentuk kemerdekaan batin dari jerat pembandingan sosial yang melelahkan. Di media sosial, kita diserbu citra-citra bahagia yang seragam: rumah rapi, tubuh ideal, wajah cerah, pasangan harmonis. Padahal realita jauh lebih berantakan. Di titik itu, syukur menjadi pemberontakan halus terhadap budaya palsu yang menuntut kesempurnaan. Ia mengajarkan keikhlasan untuk menjadi manusia biasa—yang tidak malu merasa cukup dengan yang ada.
Dalam perspektif Islam, Nabi Muhammad ﷺ memberi teladan luar biasa dalam bersyukur, bahkan dalam penderitaan. Dalam sebuah riwayat, ketika ditanya mengapa beliau beribadah begitu lama hingga kakinya bengkak, Nabi menjawab, “Afalā akūnu ‘abdan syakūra?” (Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?).* Sebuah jawaban yang sederhana, tapi mengguncang kesadaran: bahwa syukur bukan ucapan, melainkan tindakan yang melampaui kenyamanan diri.
Kini, ketika dunia dilanda krisis multidimensi—ekonomi, ekologi, hingga spiritual—bersyukur menjadi perlawanan yang lembut namun mendalam. Ia mengubah fokus kita dari keluhan menjadi kontribusi, dari krisis menjadi kesempatan. Orang yang bersyukur tidak mudah menyerah, karena ia tahu setiap musibah menyimpan potensi pertumbuhan. Dalam bahasa psikologi Islam, ini disebut coping spiritual—kemampuan untuk mentransformasikan penderitaan menjadi pelajaran makna.
Bersyukur juga mengajarkan kecerdasan moral: bahwa manusia tidak hanya hidup untuk menuntut, tapi juga memberi. Bahwa menjadi hamba yang bersyukur berarti menjadi manusia yang sadar perannya dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang cenderung menilai segala sesuatu dengan ukuran materi dan posisi, sikap syukur mengingatkan kita bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tapi oleh keluasan hatinya.
Hikmah yang dapat dipetik:
- Bersyukur bukan sekadar ekspresi religius, tetapi fondasi kebijaksanaan hidup.
- Syukur adalah kekuatan spiritual untuk menolak ekstremisme dan kebencian sosial.
- Bersyukur membuat manusia tangguh menghadapi krisis dengan kesadaran, bukan kemarahan.
- Dalam setiap perbedaan dan kesulitan, selalu ada ruang untuk menemukan makna.
- Agama yang memberi bobot dan makna, sebagaimana dikatakan Gus Paox Iben, adalah agama yang menghidupkan, bukan menakutkan.
Pada akhirnya, bersyukur adalah seni bertahan dalam badai tanpa kehilangan arah. Ia mengajarkan kita untuk menatap dunia bukan dari sisi gelapnya, tetapi dari cahaya kecil yang masih menyala di dalam hati. Sebab selama masih ada syukur, selalu ada harapan; dan selama masih ada harapan, kita tidak akan pernah benar-benar kalah—meski dunia tampak berisik, meski krisis datang silih berganti.
Bersyukur adalah bahasa jiwa yang paling jujur: tenang, lembut, tapi luar biasa kuat.

Penulis/Akademisi