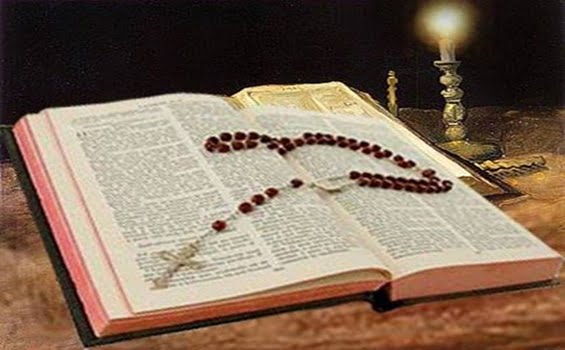Menyimak uraian perkuliahan Prof. Sahin Acikgoz dalam Mata Kuliah ”Islam and Feminisme” dengan Tema ”Dekonstruksi Otoritas Penafsiran: Dari Logika Setan hingga Patriarki dalam Membaca Teks Suci” dapat disimpulkan bahwa proyek memahami teks suci tidak bisa dilepaskan dari kesadaran linguistik, historis, dan etis yang mendalam.
Pertama, pada tataran bahasa, Prof. Acikgoz menegaskan bahwa bahasa bukanlah cermin pasif realitas, tetapi konstruksi ideologis yang membentuk cara kita berpikir dan memahami dunia. Karena itu, setiap penerjemahan dan penafsiran teks suci tidak pernah benar-benar netral. Ia selalu beroperasi di dalam “ekosistem makna” yang diciptakan oleh budaya dan kekuasaan. Bahasa menjadi medan tarik-menarik antara upaya mencari kebenaran dan kecenderungan mempertahankan dominasi. Namun, hermeneutika memberi ruang bagi manusia untuk tetap mencari makna dengan kesadaran kritis bahwa setiap penafsiran adalah hasil dialog antara teks, konteks, dan penafsir.
Kedua, dilema antara partikularitas dan universalitas teks suci menunjukkan bahwa wahyu selalu berinteraksi dengan konteks sejarah. Al-Qur’an turun di tengah masyarakat yang spesifik, namun mengandung nilai-nilai yang menuntun pada universalitas etika. Tantangan umat beragama masa kini bukanlah meniru bentuk lahir teks, tetapi menyuling esensi moral dan nilai kemanusiaannya agar tetap relevan dalam lintasan zaman. Dengan demikian, tafsir tidak boleh berhenti pada “apa yang tertulis,” tetapi harus bergerak menuju “apa yang dimaksudkan” oleh teks dalam terang kemaslahatan manusia modern.
Ketiga, konsep “Logika Setan” menjadi metafora teologis yang amat tajam dalam mendekonstruksi akar penindasan. Dalam pandangan Prof. Acikgoz, keangkuhan Setan yang merasa lebih unggul karena unsur penciptaannya adalah bentuk awal dari arogansi ontologis—klaim superioritas berdasarkan faktor yang tidak dapat dipilih. Logika inilah yang kemudian menurun menjadi struktur sosial seperti patriarki, rasisme, dan kolonialisme, di mana satu kelompok merasa lebih berhak mendominasi yang lain. Dengan demikian, membaca teks suci berarti juga membaca ulang relasi kekuasaan yang tersembunyi di baliknya, agar manusia dapat kembali kepada prinsip kesetaraan ontologis yang diamanahkan Tuhan.
Keempat, kesadaran akan kritik otoritas dan ambiguitas makna mengantar kita pada etika intelektual yang paling tinggi: kerendahan hati. Tidak ada teks—bahkan teks suci sekali pun—yang hadir tanpa medan tafsir. Kebenaran tidak berhenti di mulut satu otoritas, tetapi lahir dari proses dialog yang berkelanjutan antara teks dan pembacanya. Pengakuan atas ambiguitas bukanlah kelemahan iman, melainkan bentuk penghormatan terhadap keluasan rahmat Tuhan yang tak terhingga dan tak terkurung oleh satu sistem makna tunggal. Dengan demikian, tugas seorang pembelajar bukanlah mengunci makna, tetapi membuka kemungkinan baru bagi makna itu tumbuh dan hidup kembali dalam konteks yang selalu berubah.
Dari ringkasan di atas, dapat kita maknai bahwa dalam perjalanan panjang tafsir, umat sering beranggapan bahwa tafsir merupakan cermin bening yang memantulkan kehendak Tuhan secara utuh. Namun, sebagaimana digugat oleh Prof. Sahin Acikgoz dalam kuliahnya, bahwa pandangan itu tidak sesederhana yang dibayangkan, ia mengingatkan bahwa bahasa bukanlah medium pasif, melainkan “ekosistem tempat realitas dibangun.”
Bahasa menurutnya, selalu menyimpan jejak ideologi dan kekuasaan—ketika seseorang menafsirkan teks suci, ia tidak sekadar menerjemahkan kata-kata, melainkan juga mewariskan pola pikir dan bias zamannya. Dengan demikian, tidak ada tafsir yang sepenuhnya objektif; setiap mufasir membawa lensa pengalaman, budaya, bahkan identitas gendernya sendiri. Tafsir karenanya, bukanlah pencarian akan “kebenaran tunggal”, tetapi ruang dialog yang hidup antara teks, konteks, dan kesadaran pembacanya.
Al-Qur’an sendiri hadir dalam lanskap sosial Arab abad ke-7 — masyarakat yang sarat struktur patriarki dan tradisi kesukuan. Banyak ayat turun sebagai respons atas realitas sosial masa itu, membawa pesan transformatif bagi masyarakatnya. Namun, jika pesan-pesan itu dibaca secara literal tanpa kesadaran historis, maka semangat pembebasan yang terkandung di dalamnya justru bisa berubah menjadi alat legitimasi bagi penindasan baru. Di sinilah pentingnya tugas seorang mufasir sejati—menyeberangkan makna wahyu dari konteks partikular menuju nilai-nilai universal yang abadi — keadilan, kasih sayang, dan kesetaraan.
Salah satu gagasan paling menggugah dari Prof. Acikgoz adalah konsep “Logika Setan.” Ia menafsir ulang kisah penolakan Iblis untuk sujud kepada Adam bukan sebagai kisah dongeng kosmis, melainkan cermin teologis dari arogansi manusia sepanjang sejarah. Ketika Iblis berkata, “Aku lebih baik darinya, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah,” sesungguhnya ia sedang menegaskan superioritas berdasarkan sesuatu yang tidak ia pilih — ”faktor tak terpilih”.
Logika inilah yang terus hidup dalam sejarah umat manusia, ia menjelma dalam bentuk-bentuk kesombongan sosial, rasial, dan gender. Ketika seseorang merasa lebih tinggi karena warna kulit, garis keturunan, atau jenis kelamin, ia sedang meniru kesombongan pertama di hadapan Tuhan. Dalam konteks ini, patriarki bukan hanya struktur budaya, tetapi juga pembangkangan teologis terhadap prinsip kesetaraan ciptaan. Prof. Acikgoz menegaskan dengan lantang, “Patriarki adalah turunan sosial dari arogansi teologis Iblis.”
Sebagai antitesis dari logika ini, Prof. Acikgoz memperkenalkan Paradigma Tefatik, yakni cara pandang yang berakar pada nilai tauhid. Dalam paradigma ini, relasi manusia dengan Tuhan bersifat vertikal—penuh kepatuhan dan penghambaan—sementara relasi antar manusia bersifat horizontal–saling menghormati dan setara. Hanya takwa yang menjadi ukuran kemuliaan, bukan atribut biologis atau sosial.
Paradigma Tefatik menegaskan bahwa feminisme Islam bukanlah produk impor dari Barat, melainkan ekspresi otentik dari tauhid itu sendiri. Sebab, inti dari tauhid adalah penolakan terhadap segala bentuk keserupaan dan pengkultusan selain Tuhan — termasuk klaim keunggulan manusia atas manusia lainnya. Dalam cahaya tauhid, kesetaraan bukan sekadar wacana sosial, tetapi manifestasi spiritual dari keesaan Tuhan.
Bagi sebagian orang beriman, perbedaan tafsir sering menimbulkan kegelisahan, seolah kebenaran harus satu dan pasti. Namun Prof. Acikgoz mengingatkan bahwa ambiguitas adalah bagian dari rahmat Ilahi. Bahasa manusia terbatas, sedangkan makna Tuhan tak bertepi. Karena itu, keragaman tafsir justru menjadi tanda kekayaan intelektual dan spiritual umat, bukan sumber perpecahan. Tidak ada otoritas tunggal yang dapat memonopoli makna Tuhan. Kesadaran inilah yang menumbuhkan kerendahan hati hermeneutik, yakni sikap bahwa menafsir bukan untuk menguasai makna, melainkan untuk mendekatkan diri kepada kebijaksanaan Tuhan.
Dalam konteks tafsir gender seperti nusyuz (pembangkangan dalam rumah tangga), bias patriarkal sering tampak nyata. Tafsir klasik umumnya hanya memandang istri sebagai pihak yang bisa nusyuz, sementara tafsir pembebasan berani bertanya: mengapa tidak suami juga diklaim bisa nusyuz? Pertanyaan sederhana ini mengguncang fondasi ideologis yang selama ini menormalisasi ketimpangan. Tafsir yang berperspektif pembebasan berupaya menghidupkan kembali ruh Al-Qur’an sebagai kitab kasih sayang dan keadilan. Ia tidak berhenti pada teks, tetapi bergerak menembus batas budaya untuk menemukan pesan universalnya—penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka ini, kesetaraan gender bukanlah tuntutan modernitas semata, melainkan panggilan moral dari wahyu yang hidup.
Prof. Acikgoz menutup refleksinya dengan peringatan mendalam, bahwa “Setiap kali manusia menolak kesetaraan, ia sedang mengulangi dosa pertama yang pernah dilakukan makhluk di hadapan Tuhan.”
Membaca teks suci dengan cahaya tauhid berarti menolak segala bentuk kesombongan—baik dalam tafsir, kekuasaan, maupun relasi sosial. Bahasa dan teks bukanlah penjara makna, melainkan medan etika dan keberanian, tempat manusia diuji untuk menafsir dengan hati yang jernih dan pikiran yang bebas dari arogansi.
Sebagai catatan akhir, bahwa tafsir yang sehat bukanlah tafsir yang membungkam perbedaan, tetapi tafsir yang menumbuhkan dialog dan cinta. Ia tidak membekukan wahyu, melainkan menghidupkannya kembali dalam denyut zaman. Sebab, rahmat Tuhan hanya hadir dalam tafsir yang adil, setara, dan berpihak pada kemanusiaan. Akhirnya pertanyaan reflektif pun menggema: Apakah kita telah membaca teks suci dengan cahaya tauhid—yang membebaskan dan menyamakan semua makhluk—atau justru masih terjebak dalam logika setan yang mengagungkan diri di atas sesama? Di sinilah sesungguhnya jihad intelektual umat Islam—membebaskan tafsir dari tirani kesombongan dan mengembalikan kemanusiaan di bawah keagungan Tuhan Yang Esa.[]

Dosen UIN Mataram/Mahasiswa Doktoral Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal