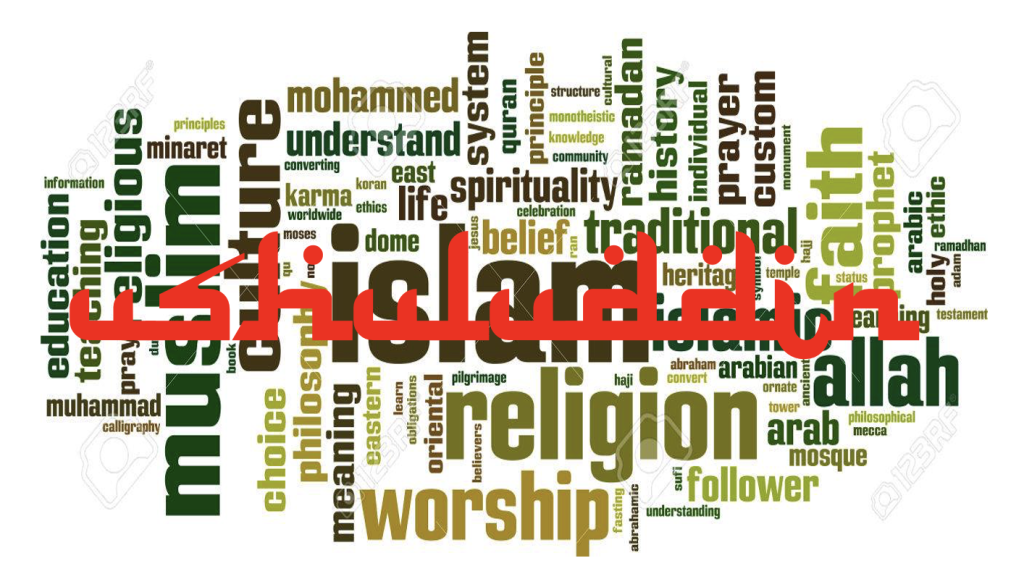USHULUDDIN, awalnya, identik dengan Ilmu Tauhid, Ilmu Aqidah atau Ilmu Kalam. Ilmu ini membahas masalah-masalah mendasar menyangkut keyakinan, seperti ke-esa-an Allah dan sifat-sifat-Nya, serta perbuatan manusia dan akibatnya. Ushuluddin adalah himpunan pengetahuan keislaman hasil perdebatan, dialektika, dan kontestasi mengenai Tuhan sebagai kesatuan ontologis-metafisis, juga mengenai akal dan wahyu sebagai piranti epistemologis.
Lama-lama, Ushuluddin bukan lagi semata-mata Teologi, Ilmu Kalam, Tafsir/Takwil/Tafsir isyari/Bathini, Tasawuf, Logika, dan Etika, tetapi wadah bagi semua itu. Ushuluddin, dalam persepsi seperti ini, mengandaikan ia sebagai sebuah pohon ilmu keagamaan yang mengalami eksternalisasi sedemikian rupa sehingga menjangkau wilayah keilmuan lain.
Karakter terbuka dan menjangkau ini dimungkinkan karena “core” Ushuluddin adalah “falsafah”, yang menjadikannya ilmu murni (pure science), yang berfungsi memberi landasan bagi penguraian persoalan-persoalan dasar umat manusia serta penerapannya dalam kehidupan dan realitas sosial (applied science).
Mengapa Ushuluddin menjadi wadah bercampuran (melting pot) bagi keilmuan Islam, terutama yang bergerak pada tataran applied science? Karena wilayah ke-Ushuluddin-an adalah pure science dengan karakter dasar falsafah. Dengan karakter dasar ini, Ushuluddin bisa memerankan diri sebagai jangkar untuk menjangkau ilmu-ilmu lain, karena ilmu-ilmu lain juga memiliki falsafah dalam dirinya.
Dengan menginstalasi falsafah dalam dirinya, maka Ushuluddin memiliki kepastian body of knowledge, yakni metafisika, epistemologi, dan etika. Jika demikian, maka Ushuluddin lebih mungkin mempertemukan pemikiran dan kajian Islam dengan tradisi-tradisi pemikiran dan filsafat Barat, juga pemikiran dan filsafat Timur lainnya. Itu pernah terjadi ketika pemikiran Islam bertemu dengan filsafat Yunani, memicu kebangkitan peradaban Islam hingga puncak kejayaannya.
Melalui karakter ini, pemikiran Islam yang lahir dan mewarnai peradaban Islam bisa mengalami fase pembebasan dari belenggu dogmatisme. Dogmatisme adalah situasi di mana falsafat diringkus dan tunduk kepada Teologi atau Kalam, sehingga diskursus Islam menjadi semata-mata Aqidah dan Syari’ah. Ini pernah terjadi pada abad pertengahan-scolastik yang diwarnai dengan kejumudan pemikiran, dan pada akhirnya menjerumuskan umat muslim dalam kemunduran yang akut.
Pertemuan dan dialog pemikiran sangat penting dan urgent dipromosikan kembali, lebih-lebih di tengah tantangan global-universal dalam era kontemporer ini. Jika tidak, maka benturan peradaban (clash of civilization) benar-benar terjadi. Hanya pertemuan dan dialog pemikiran yang bisa memberi harapan bagi perdamaian dunia, keadilan sosial, dan problem humanities di berbagai belahan dunia.
Membebaskan dan Memimpin Perubahan Sosial
Kebutuhan akan pembaharuan pemikiran dan gerakan keagamaan di dunia Islam adalah niscaya. Tetapi itu harus difasilitasi dan dilandasi oleh definisi situasi masyarakat Muslim dalam konteks pergaulannya dengan peradaban dunia. Definisi ini adalah komponen raison d’etre dari pengembangan suatu bidang keilmuan.
Perkembangan Fakultas Ushuluddin di beberapa negara muslim, khususnya di Indonesia, menunjukkan bahwa raison d’etre tidak ditinggalkan, meskipun juga tidak terlalu gamblang diungkapkan. Di Indonesia, paradigma integrasi, interkoneksi, multidisplin, interdisiplin, transdisiplin (I-kon-MIT), mendapat tempat yang istimewa dalam kajian Islam di Indonesia dewasa ini, berkat ketekunan dari Prof Amin Abdullah dan mazhabnya.
Di beberapa, kalau bukan semua, Fakultas Ushuluddin dan … (dengan berbagai nomeklatur yang berbeda-beda) di Indonesia, jargon yang mengindikasikan paradigma I-kon-MIT terinstalasi dalam tradisi studi Islam di Indonesia, terasa sangat kuat.
Sebagai contoh, UIN Jakarta menekankan integrasi ilmu keislaman dengan sains dalam skala Asia Tenggara, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) UIN Yogjakarta tentang integrasi ilmu ke-Ushuluddin-an dengan keilmuan (lain) untuk peradaban, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI) UIN Sumatera Utara mengarahkan kepada semangat multikulturalisme dan kewiraswastaan (entrepreneurship), Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) IAIN Pare-Pare menekankan pada akulturasi budaya, teknologi informasi, dan kajian kawasan.
Berpijak kepada paradigma itu, rata-rata Fakultas Ushuluddin di Indonesia melakukan lompatan-lompatan, yang kadangkala begitu besar dan jauh, terlihat dari jargon-jargon dalam visi-misi fakultas. Visi-Misi ini sungguh trendy, dalam arti mengikuti kecenderungan kultur, terutama kultur digital. Sebagian lagi mengikuti trend pasar dan lapangan kerja. Memang, adaptasi budaya akademik penting untuk memastikan “Islam” yang inheren dalam Ushuluddin “shalih likulli makanin wa zamanin”.
Dengan ini juga, jika ada pertanyaan apakah Ushuluddin masih relevan? Maka dengan lugas kita bisa jawab, ya, sangat relevan! Maka, Ushuluddin yang kita lihat sekarang adalah Ushuluddin yang mulai grinta, lincah merambah dan bersentuhan dengan wilayah keilmuan lain, pun keilmuan-keilmuan tandem itu berbasis falsafah Barat atau Timur lainnya.
Hanya saja, dengan ini orang masih bisa menggugat, lalu apa beda Ushuluddin dengan keilmuan-keilmuan terapan yang kebanyakan terjebak pada kapitalisme-pragmatisme sosial-kebudayaan, yang melanggengkan kesenjangan dan mereproduksi ketidakadilan, serta ikut melakukan dehumanization of society?
Padahal, Ushuluddin yang kita bayangkan, libati, dan kembangkan adalah Ushuluddin yang harusnya memimpin perubahan sosial dan pembebasan. Pembebasan dari dogmatisme sains modern (saintisme) dan pembebasan dari struktur sosial yang timpang. Ushuluddin harus bebas dan membebaskan dari “tawanan dogmatisme yang dibuat sendiri.”
Maka lompatan yang dibuat boleh jauh dan besar, dan itu harus, tetapi jangan sampai tidak berpijak pada falsafah. Falsafah ini memberi perspektif bagi pendefinisian sebuah realitas dan basis struktur yang melandasi perubahan sosial. Falsafah memberi dasar rasionalitas yang akan menghasilkan perubahan besar dalam kehidupan sosial.
Itu yang terjadi pada dunia Barat, dengan falsafah mereka memasuki era pencerahan (enlightenment) yang memicu perubahan mendasar terhadap cara memandang alam semesta (world view), melahirkan sistem budaya baru. Mereka lalu memasuki fase perubahan dan kemajuan sosial, bernama modernitas. Dan modernitas merambah ke seluruh aspek kebudayaan dan peradaban dan memetamorfosa dalam kehidupan kontemporer ini.
Internalisasi dan Eksternalisasi
Sekarang, ada introspeksi diri mengenai kondisi intelektualisme dunia muslim yang kini dinilai mengalami kemunduran akut. Dari sini muncul kritisisme tentang belum bekerjanya ilmu-ilmu, terutama ilmu sosial, humaniora, juga Islamic Studies dalam membaca dan mengelola perubahan sosial. Lalu muncul upaya revitalisasi studi Islam, ilmu sosial, sosiologi, antropologi, dan sebagainya yang bekerja dalam konsolidasi potensi umat untuk mobilisasi, gerakan, dan perubahan sosial.
Kita sedang serius mencari pintu liminal, yakni celah untuk keluar dari anomali yang meskipun wilayah baru belum tertentukan. Ushuluddin, dengan kerja ilmu dan intelektualisme yang tersofistikasi, kiranya bisa maju dalam mengayuh jalannya sejarah umat manusia, khususnya dunia Islam.
Melalui kerja intelektualisme ke-Ushuluddin-an yang khas, sarjana-sarjana Ushuluddin menjadi terbuka untuk berdialog dengan berbagai perspektif dan mazhab pemikiran. Mereka bisa bertemu dengan tradisi positivisme Amerika, empirisme Inggris, rasionalisme Perancis, kritisisme Jerman, dan sebagainya.
Sekarang, kita butuh Ushuluddin yang memiliki ciri “focusing inward, opening outward”. Mari kita namai “Ushuluddin Baru”. Yakni Ushuluddin yang solid ke dalam dan memancar keluar. Fokus ke dalam dengan melakukan internalisasi inti ajaran agama Islam dan falsafah beserta variannya. Setelah itu mengalami eksternalisasi, membuka diri untuk masuknya kekayaan keilmuan lain sambil menawarkan khazanahnya untuk mewarnai raison d’etre keilmuan masing-masing.
Ushuluddin baru ini digadang untuk mengemban tugas sebagai penggugah kesadaran masyarakat muslim akan nilai-nilai baru, penerimaan sosio-kultural atas nilai-nilai dan praktik-praktik baru, dan adaptasi metode dan cara kerja baru dalam produksi pengetahuan dan pemecahan masalah.
Sarjana Ushuluddin utamanya pemikir yang menjangkau universalitas fenomena, bukan sekedar spesialis yang berurusan dengan partikularitas. Yang terakhir ini, tugas dan porsi ilmuwan yang bergerak dalam bidang ilmu terapan. Sarjana Ushuluddin sejatinya adalah ideolog dan aktor bagi perubahan sosial. Mereka raushan fikr, intelektual organik dan profetis, arsitek dan pemimpin (leader) bagi masyarakat.[]
*Diolah dari Prasaran untuk Forum Dekan Ushuluddin se-Indonesia 2023 dan The First Annual International Conference on Religion and Sosial Studies (AICRS), Mataram 18 Mei 2023.

Pengkaji agama dan budaya, direktur Alamtara Institute dan founder Kalikuma Library & EduCamp NTB