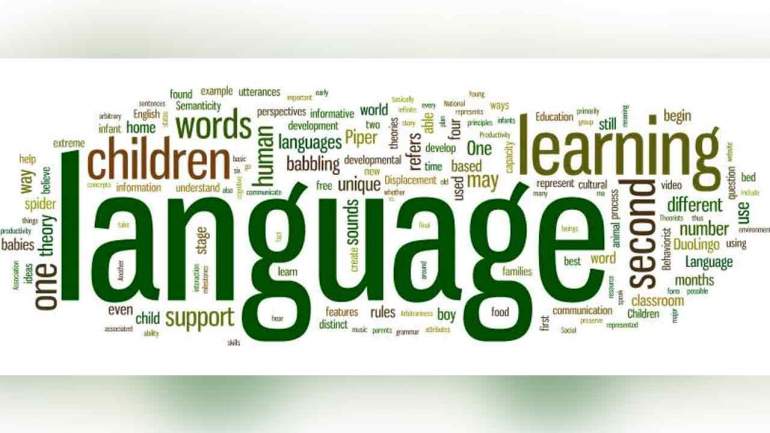DI media sosial ada yang menyebut nama “Mbojo” ini dinilai “keliru dan menyesatkan”, Muslimin Hamzah yang menulis catatan itu beralasan, penamaan Suku Mbojo itu mengada-ada, keliru dan menyesatkan orang Bima. Dia menilai penamaan Mbojo tersebut merupakan ulah segelintir oknum bangsawan Mbojo/Mbojo Nae/Rasanae yang terobsesi oleh kebesaran masa lalu mereka.
Padahal, menilik sejarahnya, sejumlah bangsawan Mbojo Nae dulu bertindak sebagai “second man” alias Londo ireng, Belanda Hitam. Mereka menganggap dirinya bayangan kolonial Belanda di Tanah Bima.
Saya tertarik membuat catatan tentang komentar Bung Muslimin Hamzah ini. Saya khawatir jika tidak diluruskan dan diberi pemahaman nanti bisa menimbulkan gagal paham tentang penamaan dan penggunaan kedua nama itu, Mbojo dan Bima di dalam masyarakat baik secara verbal ataupun tulis.
Kita perlu pahami, nama merupakan kata untuk menyebut atau menyimbolkan sebuah benda, termasuk orang. Kata adalah komponen terkecil dari bahasa yang memiliki makna. Merujuk pada apa yang dikatakan oleh Socrates (Josep, 2009: 16) bahwa bahasa itu lahir dari alam dan ilmiah. Berdasarkan pada alam, manusia kemudian memberi nama terhadap sesuatu sesuai keadaan tempat dan saat terjadinya sesuatu.
Memang William Shakespeare pernah menyebut, “What is a name?” (Apalah arti sebuah nama). Sebab, kalau kita menyebut ‘kamboja’ tetaplah dia disebut kembang. Tetapi bagi kita di Timur, nama adalah identitas dan juga doa.
Kata dan bahasa adalah “rumah tanda” karena tidak ada kemungkinan ada yang mengada di luar bahasa, sehingga kata dan bahasa pun menjadi rumah kehidupan. “Language is the house of being,” kata Heidegger (Josep, 2009: 30).
Di dalam ilmu linguistik disebutkan, lahirnya suatu bahasa karena melalui proses konvensi, kesepakatan antarpemakai bahasa. Kita memberi nama terhadap sesuatu karena ada kesepakatan di antara para pemakai bahasa itu menggunakan satu nama atau kata tersebut.
Misalnya, mengapa kita bangsa Indonesia memberi nama ‘radio’ pada pesawat radio yang merupakan produk bangsa asing tetap sesuai dan sama dengan nama bawaan benda itu karena para pemakai bahasa Indonesia sepakat nama lain untuk menyebut benda itu tidak ada. Sehingga, tetap digunakan nama bawaan yang menyertai benda tersebut.
Mengapa di dalam bahasa Indonesia menggunakan vokal /i/ untuk kata /bikin/ dan tetap membacanya /bikin/. Itu karena kesepakatan pemakai bahasa. Bandingkan dengan bahasa Inggris, vokal /i/ dapat dibaca /ai/ Misalnya pada kalimat “I like it” harus dibaca “Ai Laik it” . Vokal dobel /ee/ justru dibaca /i/. Contohnya,”I see you” (Ai si yu). Perbedaan penggunaan vokal dan pengucapannya yang berbeda dalam kedua bahasa tersebut terjadi karena berdasarkan kesepakatan para pengguna bahasa itu.
Lantas merujuk pada nama “Mbojo” para leluhur Bima sepakat untuk memberi nama itu pada daerah yang kemudian juga memiliki nama lain jika diucapkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Bima. Pemberian nama Bima merujuk pada pandangan Socrates itu, yang menyebutkan bahwa kata itu lahir dari situasi alam yang terjadi pada masa itu. Lahir sesuai dengan keadaan yang dibawa oleh seorang yang bernama Sang Bima itu. Kita tidak pernah protes selama ini.
Adalah sangat keliru menggugat penamaan yang sudah diterima oleh masyarakat sejak dulu dikoreksi dengan pandangan kritis kita saat ini beralasankan hal yang ‘remeh temeh’. Hanya karena tidak ada di dalam berbagai buku, termasuk yang ditulis oleh orang Belanda.
Di dalam naskah La Galigo (Transliterasi Jilid II, 2000) dan “Lontarak Bilang, Raja Gowa dan Tallok” (Transliterasi 1985/1986) dalam naskah asli berbahasa Bugis dan Makassar kuno disebutkan “Gima” yang kemudian dipahami sebagai Bima. Kata “Mbojo” sendiri secara etimologis sudah jelas terungkap sebagaimana ditulis oleh Ahmad Amin (1971) yang kemudian dikutip oleh banyak penulis buku jika menyoal muasal nama “Mbojo”.
Penulis juga memberikan analogi sekitar nama Makassar, juga lahir dari proses situasi dan peristiwa alam seperti ini. Dalam catatan Wahid (2007: 20-21) disebutkan, pada zaman dulu ada seorang ulama yang telah menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan bernama Abdul Kadir Khalib Tunggal Dato ri Bandang. Ia berasal dari Minangkabau, Kota Tengah, di Sumatra Barat. Dia pernah menuntut ilmu di Jawa Timur, menjadi murid Walisongo, yakni Sunan Giri.
Dato ri Bandang tiba di Makassar, tepatnya di Pelabuhan Tallo, bagian utara Kota Makassar sekarang, menumpang perahu pada tahun 1605, saat orang Sulawesi Selatan mulai menganut agama Islam. Setibanya di pelabuhan, dia menunaikan salat yang membuat orang yang menyaksikannya terheran-heran.
Setelah mendengar berita itu, Raja Tallo bergegas ke pantai, walaupun suasana pagi masih gelap. Dalam perjalanan menuju pelabuhan, di depan gerbang halaman istana, Baginda bertemu dengan seorang laki-laki bersorban hijau dan berjubah putih. Orang tersebut menjabat tangan Baginda, kemudian menuliskan kalimat syahadat di tangannya.
“Perlihatikan telapak tangan Baginda kepada pendatang yang disangka orang ajaib itu!,” ujar orang berjubah tersebut lalu raib dan gaib.
Setelah tiba di tempat pendatang menambatkan perahunya, Baginda melakukan apa yang dipesankan orang yang menemuinya di gerbang istana.
“Tahukah Baginda siapa gerangan yang menulis di atas telapak tangan Baginda?,” orang berjubah itu bertanya.
“Tidak!,” Raja Tallo menjawab singkat.
“Baginda sudah menerima Islam dari Rasulullah Saw sendiri karena yang menemui Baginda niscaya adalah Nabi Muhammad Saw yang menjelmakan diri di negeri Baginda,” pendatang itu menjelaskan.
Mengetahui peristiwa tersebut, orang Tallo kemudian mengatakan “Makkassaraki” Nabbia (nabi menampakkan diri). Dari kata inilah asal nama nama Mangkassaraki lalu Mangkasara hingga menjadi Makassar.
Sampai sekarang orang Makassar tidak pernah menggugat kata “Mangkasara” dalam percakapan sehari-hari dengan alasan bahwa yang sah adalah Makassar. Sebab, kedua nama itu ditempatkan sesuai proporsinya. Kata Mangkasara bisa digunakan pada nama seperti “Coto Mangkasara” ‘Tau Mangkasara” (orang Makassar),” “Batu ri Mangkasara” (Datang dari Makassar) meskipun ada yang juga menulis “Coto Makassar”. Silakan dipakai.
Sama dengan Mbojo, mengapa tidak satu pun ada dalam buku, meskipun dalam buku yang ditulis oleh sejarawan Bima sendiri kata itu disebutkan. Hal itu disebabkan, nama Bima digunakan dalam komunikasi yang menggunakan bahasa Indonesia, yaitu dalam komunikasi formal dan dalam penulisan ragam baku.
Sementara kata “Mbojo” konteksnya digunakan secara lokal, yaitu secara internal oleh masyarakat Bima yang berdiam di daerah yang berbahasa Bima dan tidak dapat berbahasa Indonesia. Jadi, jelas porsi penggunaannya secara fragmatik di dalam masyarakat.
Akan sangat lucu jika kita berbahasa Indonesia menulis kalimat yang berbunyi,” Saya mau ke Mbojo besok”. Kalimat ini tidak berterima sebab padanan yang benar adalah “Saya mau ke Bima besok”.
Saya kira tidak ada orang Bima yang memprotes penggunaan kedua nama itu sesuai proporsinya, ya tentu kecuali Bung Muslimin Hamzah. Kita tidak bisa menafikan dalam komunikasi verbal warga Bima jika menggunakan bahasa Bima (nggahi Mbojo) jelas akan menggunakan “nggahi Mbojo”.(Saya menulis kalimat ini saja rasanya jadi lucu karena terjadi ‘campur kode” – penggunaan dua bahasa dalam satu kalimat).
“Wati lao mu do Mbojo ro?” (Apakah Anda tidak ke Bima).
Tidak mungkin kita menulis:
“Wati lao mu do Bima ro?”.
Nama “Mbojo” sudah mendarah daging dalam komunikasi antarpersona orang Bima. Orang Bima yang tuna-aksara dan tidak tahu berbahasa Indonesia, jelas akan menggunakan bahasa pengantar “nggahi Mbojo”, (Selengkapnya catatan saya megenai ini kelak dapat disimak di dalam buku saya yang akan terbit “To Manurung-Ncuhi & Sawerigading-Sang Bima (Relasi Mitologis Sulawesi Selatan dan Bima).
Saya sangat yakin kalau orang Bima dilarang “nggahi Mbojo” akan berontak. Percayalah.[]
Ilustrasi: Sukabumi Update

Akademisi Universitas Hasanudin, penulis dan jurnalis yang tinggal di Makassar