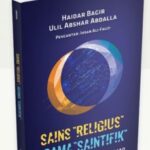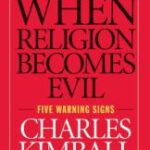Saat kemping di Sarae Nduha awal Juni lalu media sosial ramai perkara sampah. Kita masih harus bekerja keras sekadar mengedukasi masalah sampah ini, apalagi di sebuah event yang dihadiri ribuan atau puluhan ribu orang.
Di Festival Lakey kita juga ribut soal sampah, tepatnya ‘sampah’ akidah. Berbeda dengan sampah benaran, ‘sampah’ akidah ini lebih rumit kayak hubungan akoh dan kamuh.
Kalau sampah di Sarae Nduha relatif mudah mengatasinya. Semua orang, baik pembuang sampah maupun panitianya, sepakat akan bahu-membahu membersihkannya.
Setelah event selesai sampah-sampah di area kemping berhasil dibersihkan. Aman.
Tapi ‘sampah’ akidah? Ini lebih kompleks karena ajaran agama bercorak interpretable. Sulit mendapatkan satu interpretasi tunggal, apalagi menyangkut hal-hal muamalah.
Di ajang Festival Lakey, sebagian orang mempersoalkan istilah ‘ritual’ dan ‘soji ra sangga’ (penyerahan sesajen) dan tarian Ou Balumba (memanggil ombak) karena dianggap bertentangan dengan semangat purifikasi dalam Islam.
Meski ini hanya sebuah kreasi seni dan pure entertain, tapi para penentang acara ini menganggapnya membahayakan kemurnian akidah Islam.
Mereka juga khawatir tarian Ou Balumba bakal mendatangkan ‘bencana’ dan kemurkaan Allah karena tergolong syirik, sedangkan syirik adalah dosa paling besar dalam sistem teologi Islam. Singkatnya gelaran tarian ini dapat merusak tauhid.
Memang, ‘negasi’ (peniadaan tuhan lain selain Allah) dan ‘konfirmasi’ (penegasan bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan) adalah spirit utama kalimat syahadatain. Secara normatif ikrar syahadat adalah tonggak penanda keislaman seorang muslim.
Secara antropologis masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama, sehingga setiap apapun pasti dihubungkan dengan agama–terutama soal dosa, pahala, hukuman dan ancaman.
Agama juga dipercaya sebagai satu-satunya sumber dan pembentuk nilai moral, termasuk dalam menegakkan tertib sosial.
Emile Durkheim mendefiniskan agama sebagai “sebuah sistem keyakinan dan praktik yang mengandaikan terbentuknya sebuah komunitas moral yang tunggal.”
Karena agama menghendaki terbentuknya “komunitas moral yang tunggal” tersebut maka agama, secara normatif, tidak membolehkan adanya versi lain di luar dirinya.
Keharusan terbentuknya “komunitas moral yang tunggal” juga secara intrinsik mendorong seseorang menjadi polisi akidah: mengklaim dirinya paling benar atau akidahnya paling murni dari orang lain. Imajinasi tentang yang ‘murni’, ‘yang tidak bercampur’, atau ‘yang asli’ dipandang sebagai puncak kebaikan dan kebenaran tertinggi dalam beragama.
Dari sini bisa dipahami muncul dan menguatnya berbagai narasi penyesatan, bidah, syirik bahkan pengafiran meski hal-hal tersebut lebih merupakan kategori sosiologis ketimbang kategori teologis.
Hal itu juga sejalan dengan penjelasan Bernard Lewis dalam bukunya “Bahasa Politik Islam” (1996) yang memandang bahwa Islam sebagai “sistem nilai” sekaligus “sistem simbol.”
Setiap sesuatu yang dinilai sebagai ‘penyimpangan’ ajaran agama akan selalu dicari rujukannya dalam kitab suci atau dalil maupun berbagai peristiwa historis di masa lalu.
Tetapi menggunakan agama sebagai satu-satunya ‘template’ menimbulkan risiko dan kesan bahwa agama tidak selalu kompatibel dengan realitas dan praktik sosial yang ada.
Itulah yang tergambar dari polemik tarian ritual Ou Balumba dimana sebagian orang menjadikan agama sebagai satu-satunya ‘template’ untuk menilai sebuah kreasi seni.
Untuk sebagian, tentu saja, menilai sebuah karya seni dengan kacamata an sich tidak selalu sejalan. Agama bercorak normatif, sementara kreasi seni mengandaikan imajinasi bebas.
Jika agama terlalu jauh mengatur apalagi mengontrol seni maka potensial menindas kebebasan berekspresi. Jika tidak hati-hati maka (interpretasi) agama dapat mengakibatkan kreasi seni menjadi sulit berkembang.
Jadi, keduanya harus saling menghormati ranah masing-masing. Sebaliknya intervensi yang terlalu jauh dapat mengakibatkan dunia kesenian terkungkung dan sulit berkembang.
Ibaratnya, jangan sampai aturan sepak bola digunakan untuk bola voli. Pasti gak nyambung.
Meski begitu agama dan praktik budaya sejatinya tidak mesti saling menegasikan tapi bisa bernegosiasi dan berelasi.[]
Ilustrasi: liputanntb.net

Akademisi, mantan wartawan kampus, dan pengagum Gandhi, “Plain Living High Thinking”.