SEMANGAT beragama yang membebaskan dalam konteks keindonesiaan tak bisa dilepaskan dari sumbangsih Prof. Nurcholish Madjid yang akrab disapa Cak Nur (lahir 17 Maret 1939 – meninggal 29 Agustus 2005). Saya tergerak untuk membuat catatan reflektif tentang cendekiawan besar itu ketika melihat semarak acara Bulan Cak Nur (Haul ke-15).
Di kanal medsos juga terdapat acara webinar yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS) bertajuk Humanisme Cak Nur. Guru Bangsa itu seolah ‘hadir’ kembali di tengah ketegangan antara sains dengan gaya beragama (sebagian) yang anti-intelektualisme, ditambah lagi gejala dehumanisasi yang merusak ikatan kebangsaan kita.
Tema humanisme Cak Nur sangat relevan untuk terus diperbincangkan dan diaktualisasikan dalam tindakan praksis untuk membela kemanusiaan. Begitu pula relevansi pemikiran Cak Nur yang mengharmoniskan antara wahyu agama dan sains, filsafat dan tasawuf, rasional dan spiritual maupun narasi besar: keislaman, keindonesiaan, kemodernan.
Pergulatan Pemikiran
Jauh melintasi waktu, saya bergelut dengan pemikiran Cak Nur lewat rute perjalanan yang agak berbelok-belok, berputar-putar, penuh lorong dan tanjakan. Sosok Nurcholis Madjid pertama kali saya dengar dari cerita ayah saya, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sebuah SDN di Kabupaten Bima, NTB. Kesan yang saya peroleh, intinya Cak Nur seorang tokoh nasional yang tidak sepenuhnya saya pahami semasa kanak-kanak.
Saat SMP, saya “merantau” ke Kota Bima. Di tengah episode pencarian jati diri, saya yang sedang mengalami puber ideologis saat remaja pernah dihadapkan dengan beberapa buku yang mengantagoniskan tokoh-tokoh seperti Cak Nur hingga Gus Dur. Saya nyaris terpapar.
Seiring perjalanan waktu, saya kemudian menemukan buku ‘berat’ di Perpustakaan Umum Daerah Bima. Judulnya Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution (Dunia Bulan Bintang, 1989), yang salah satu kontributornya adalah Cak Nur. Ketika membaca uraian Cak Nur yang memukau, saya merasa tercerahkan.
Kita diperkenalkan dengan istilah-istilah canggih dalam blantika pemikiran keagamaan dengan logos dan etos yang kuat. Sentuhan spiritual Cak Nur kian terasa ketika sebuah makalah saya dapatkan dari seorang paman (pengamal tarekat) berjudul “Peran Tasawuf dalam Membentuk Masyarakat Cinta Damai”, yang salah satu kontributornya Cak Nur.
Perjumpaan antara alam falsafah Cak Nur dengan renungan sufistik akhirnya menjadi benteng yang kuat dalam membendung arus ekstremisme. Gairah intelektual tambah membara tatkala mondok di HMI, kemudian membaca Cak Nur. Saat mengikuti Basic Training di HMI Cabang Makassar Timur, Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (NDP) yang disusun oleh Cak Nur sangat berarti dalam perjalanan intelektual-spiritual saya.
Para calon kader ditekankan untuk menguasai kunci pengetahuan melalui filsafat ilmu. Segala sesuatu ditelaah berdasarkan kerangka berpikir ilmiah dan critical thinking. Dalam tradisi berpikir kritis dan rasional di training HMI, saya pribadi merasa terselamatkan dari ancaman bigotri.
Asyiknya, pemateri menggunakan metode dekonstruksi (pembongkaran). Perdebatan intelektual dilakukan secara objektif dan sistematis yang dikemas dengan gaya dialog dalam iklim dialektika yang cair dan egaliter. Dari Cak Nur itulah saya membatinkan spirit Islam yang cair, terbuka, cinta damai lintas batas dan menghargai akal sehat.
Saya yang semula agak ‘kaku’, lambat-laun menjadi terbuka. Saya pun bertumbuh ‘sehat’ berkat tanah subur Hijau-Hitam, hingga menghirup berbagai mozaik pemikiran segar yang kita serap dari berbagai arah mata angin.
Sebuah catatan yang menarik dari akademisi yang juga aktivis perdamaian NTB, Dr. Atun Wardatun, terkait karya-karya Cak Nur yang ternyata dipahami salah oleh sebagian orang.
“Banyak tulisan yang mereduksi pemikiran beliau (Cak Nur) sedemikian rupa sehingga terkesan sangat “sekuler” padahal sangat religious setelah membacanya langsung dan menarik benang merah dari semua karyanya tersebut”, tulis Atun Wardatun di laman facebooknya.
Poinnya adalah, kita ditekankan bagaimana menjadi seorang muslim yang inklusif dan menghargai keberagaman. Pesan-pesan pembebasan, kemanusiaan, integrasi antara wahyu dan akal harus menjadi panduan bagi kita. Sehingga kita sampai pada satu fase yang membentuk jiwa merdeka.
“Saya sebagai mahasiswa yang dulunya ber-PMII, merasa menjadi “a new kid outside the block” berada se-flyer dengan para mahaguru yang punya nama besar dalam rangkaian kegiatan bulan Cak Nur ini”, ungkap Atun Wardatun yang menjadi salah satu pembicara dalam peluncuran Karya Lengkap Cak Nur (bersama M. Wahyuni Nafis dan Budhy Munawar-Rachman) pada 26 Agustus 2020 lalu.
Menjadi Bintang Caknurian
Ketika akal dipinggirkan dan dogmatisme-fanatisme buta menggerogoti nalar, maka spirit Cak Nur harus dihadirkan kembali. Ketika ujaran takfiri berkumandang dan kekerasan atas nama agama memenuhi ruang publik, menjadi bintang Caknurian adalah sebuah panggilan sejarah untuk menyampaikan risalah Islam yang membebaskan, demokratik dan humanis.
Para Caknurian mesti meneruskan pembaharuan untuk mengarus-utamakan Islam sebagai api, bukan abu. Api Islam Cak Nur dimaksudkan sebagai upaya mempertajam warisan ‘berkemajuan’ dari para pendahulu seperti Bung Karno. Dengan begitu, kita bisa mendobrak kebekuan dan menyegarkan intelektualitas.
Di antara output-nya adalah kesadaran akan pluralitas kemajemukan agama, etnik, dan sosio-kultur sebagai kenyataan, lalu mencari titik temu (kalimatun sawa) sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Sumbangsih gagasan Cak Nur seputar demokrasi, HAM, moralitas politik, pluralisme adalah sesuatu yang berharga untuk menciptakan keadaban publik. Cakrawala ide-ide Cak Nur itu dapat diringkas ke dalam tiga lelaku: beriman, berilmu, dan beramal.
Di sinilah posisi strategisnya bintang Caknurian yang tersebar di berbagai daerah untuk mengartikulasikan pesan-pesan keagamaan universal secara progresif dan kontekstual di zaman now ini.
Sebagai contoh, di NTB terdapat komunitas epistemic bernama Alamtara Institute yang didirikan oleh salah satu “anak ideologis” Cak Nur, alumni HMI: Dr. Aba Du Wahid. Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram itu kemudian melahirkan alamtara.co sebagai wadah para “kyai digital” untuk berbagi, menerangi cakrawala di Bumi Gora – tidak hanya untuk NTB, tapi juga untuk Indonesia dan dunia, rahmatan lil-alamin.
Oleh sebab itu, pelbagai pewaris intelektualitas Cak Nur baik yang bersemayam di HMI, Muhammadiyah, NU maupun kaum nasionalis lainnya memiliki obligasi moral untuk melanjutkan, memperkaya, mempertajam dan mengontekstualisasikan warisan Sang Pembaharu itu. Kekuatan simpul Caknurian mesti terdepan menjaga nalar publik, memancarkan cahaya Islam yang mencerahkan dan memberdayakan, terutama di daerah-daerah. Mari berikhtiar menjadi bintang Caknurian.[]
Ilustrasi: minews.id

Alumnus Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS, Makassar; peneliti di Charta Politika Indonesia, pernah bergabung di BNPT, serta aktif dalam kegiatan riset seputar komunikasi politik, hubungan internasional, dan dinamika politik domestik.

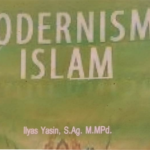




Pingback: ‘Melawan’ Cak Nur | alamtara.co